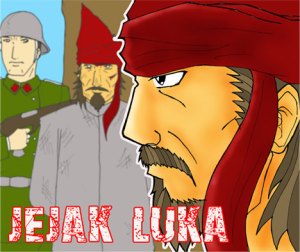Tahun 1908, tujuh hari setelah ayah dimakamkan. Serdadu Kompeni datang kembali menjemputku ke Kampung Tapi. Mau tak mau aku harus pergi, aku khawatir kampung ini juga akan dimusnahkan kalau aku tak turuti kemauan mereka. Kini, Maya sudah tanpak agak tenang dari pada pertama kali aku dijemput beberapa hari lalu. Sebelum aku pergi dia masih sempat menyuguhkan kopi.
“Jangan buru-buru, Da, minumlah kopi ini, entah kapan lagi aku akan membuatkan kopi untuk Uda[1].”
Nisa kecil pun menimpali kata-kata ibunya.
“Minumlah, Bapak. Nisa sayang Bapak, Nisa akan tunggu Bapak pulang.”
“Anakku…sudah tak sanggup Bapak untuk meminumnya, semakin lama Bapak di sini semakin marah mereka kepada kita, Bapak tidak mau kampung ini seperti Kampung Bansa.”
Walau bagaimanapun juga, aku minum kopi buatan istriku. Aku tinggalkan Maya dan Nisa, tapi mereka mengiringi dari belakang disertai uraian air mata yang membuat hatiku luka. Sesampai di simpang jalan, aku tidak kuasa melihat anakku menangis sambil memeluk ibunya. Saat aku melihatnya, dia kejar pelukanku seperti untuk terakhir kalinya dia akan bertemu denganku.
“Bapak…aku ikut dengan Bapak.”
“Pulanglah, Nak, temani ibumu, jaga dia baik-baik. Kalau Nisa pergi, dengan siapa ibu kan ditinggalkan?”
“Tidak, Bapak, kami akan pergi dengan Bapak apapun yang akan terjadi pada Bapak.”
“Pulanglah, Sayang.”
“Tidak guna lagi kami hidup tanpa Uda.”
Tanpa kuduga ternyata Maya sudah berada di samping kami, aku berdiri menatap matanya yang luka.
“Jangan bicara seperti itu, pulanglah ke rumah, berdoa kepada Tuhan.”
Anak dan istriku akhirnya pulang, setelah aku dibawa kompeni. Terasa sakit berpisah kasih sayang. Setelah lama berjalan diiringi serdadu, kami sampai ke sebuah gudang. Saat itu matahari sangatlah panas, aku disuruh masuk ke dalam gudang itu. Aku kira Komendur Westenenk yang berada di dalam gudang itu, ternyata dia tidak ada, hanya ada beberapa orang serdadu. Aku tidak tahu entah apa salahku hingga dibawa ke sini.
Cukup lama di dalam gudang, seorang sipir penjara datang dan bertanya kepadaku.
“Haji Ahmad?”
“Iya!” jawabku tegas.
“Mengapa kakimu?”
Aku tidak menjawab pertanyaan yang tidak berbobot itu, dia sudah tahu kalau kakiku ini sedang terluka. Ternyata aku benar, itu hanya basa-basi tak laku sebagai pembuka kata-katanya. Setelah itu dia langsung ke maksud tujuannya.
“Haji Ahmad, kamu dinilai sebagai orang yang akan membahayakan Belanda, jadi untuk sementara kamu ditahan.”
“Membahayakan…? Apa yang aku lakukan sehingga aku dinilai membahayakan untuk Belanda…?”
“Kamu sering ceramah dan menghasut masyarakat.”
“Ah…kalian sudah dihantui rasa takut yang kalian ciptakan sendiri, sehingga melihat aku mengajar mengaji kalian anggap sebagai hal yang berbahaya. Kalau kalian tidak melakukan kesalahan-kesalahan tentu hal ini tidak akan terjadi.”
“Tidak usah banyak bicara, Haji Ahmad, yang penting kamu ditahan, apapun alasannya.”
Aku tercenung oleh kata-kata sipir penjara itu. Tapi walau bagaimanapun aku sudah bertekad untuk menghadapi apapun yang akan terjadi. Termasuk kejadian terburuk sekalipun. Menyaksikan aku sudah diam, sipir senjara memerintahkan kepada opas untuk segera memasang belenggu di tanganku dan memerintahkan untuk membawaku ke Bukittinggi. Untuk perintah yang kedua itu aku segera membantah.
“Tak usah aku dibelenggu, perintahkan saja akan kalian bawa ke mana aku.”
Sipir penjara itu seolah-olah tidak mendengar kata-kataku. Dia tidak menarik ucapannya sehingga seorang opas mendekatiku dengan sebuah belenggu.
“Untuk apa aku akan dibelenggu, tidak usah, aku tidak akan lari.”
Setelah berkata seperti itu aku mengambil sebuah kursi lalu duduk di atasnya. Saat aku duduk, sipir merasa aku akan mencoba-coba kemarahannya.
“Wow…mau coba-coba denganku ya…”
Sipir itu berjalan mondar-mandir sambil memutar kumisnya yang lebat. Saat dia berputar-putar, datang seorang serdadu. Serdadu itu diperintahkan oleh sipir untuk menjagaku.
“Dia tidak mempan peluru, Tuan.”
Mendengar pengakuan serdadu itu aku jadi kaget, mengapa dia sampai bicara seperti itu? Ternyata mereka benar-benar dihantui ketakutan sendiri, sehingga memandang berbahaya semua orang, bahkan aku dianggap keramat tak mempan peluru, entah dari mana dia menyimpulkan hal itu. Apakah dia pernah datang ke Kampung Bansa dan ikut serta membunuhi orang-orang kampung dan ayahku? Atau mereka hanya sekedar mendengar ketakutan-ketakutan temannya saja. Seketika bergetar imanku mendengar kesaksian serdadu itu.
Ketika pendul jam berdentang satu kali menandakan hari pukul satu, hujan mulai turun. Aku tidak jadi dibawa ke Bukittinggi. Serdadu dan sipir penjara meninggalkanku. Aku tinggal dalam gudang seorang diri. Seperginya dua orang Belanda itu, datang seorang serdadu lain menemaniku. Hujan semakin lebat. Aku berdiri ke beranda gudang. Serdadu yang menemaniku itu membawa kursi untukku yang memandang hujan mengguyur Negeri Kamang.
“Terima kasih.”
Serdadu itu mengangguk sambil tersenyum, mencoba mengakrabiku. Aku duduk di kursi yang disediakan serdadu itu. Hatiku yang tidak menentu mulai terasa sunyi melihat hujan yang semakin deras.
Saat aku bermenung menatap hujan, seorang sersan Belanda memberikan rokok daun nipah padaku. Mungkin dia kasihan padaku yang terasa sepi. Sesaat dia meraba-raba saku celana dan saku bajunya. Mungkin dia sedang mencari korek api. Menyadari benda itu tidak ada padanya segera dia meminta pada serdadu yang manjagaku.
“Tidak usah, terima kasih. Aku tidak merokok.”
Sersan itu tak jadi memberikan rokok padaku, dia masukkan rokok yang telah dilenting itu ke dalam mulutnya, lalu menyulut dengan api yang telah diberikan temannya.
“Punya anak?”
Sersan itu bicara dalam bahasa Melayu yang sangat buruk, mencoba merintang hatiku yang sedang gamang. Aku jawab dengan pendek.
“Punya.”
“Berapa orang?”
“Satu orang?”
“Satu orang? Biasanya orang terhormat punya anak yang banyak dari istri yang juga banyak?”
“Tidak semua,“
“Aku juga sudah punya anak, tiga orang, sekarang mereka aku tinggalkan di Belanda bersama istriku.
(Bersambung)